Kali ini ingin kusampaikan sepenggal cerita pilu dari sahabatku Riri. Dia bertutur tentang salah satu episode paling menguras emosi dalam hidupnya. berikut kisahnya.
Aku Riri. Aku anak ketiga dari empat bersaudara yang kebetulan adalah perempuan semua. Keluargaku sederhana. Kami tinggal di penghujung pulau Jawa.
Meskipun dari keluarga biasa-biasa saja tapi hidupku ini penuh dengan ambisi. Semasa sekolah aku selalu aktif berorganisasi, bahkan aku juga termasuk siswi berprestasi. Berbagai kejuaraan dan kompetisi berhasil kujuarai.
Teman-teman bahkan para guru senang sekali bergaul denganku. Mereka menganggapku anak yang ceria. Memang dihadapan mereka aku selalu berusaha terlihat gembira, tapi bukan berarti hidupku mulus-mulus saja. Mereka saja yang tak tahu bagaimana hidupku sebenarnya. Karena memang kepada mereka aku lebih senang berbagi suka ketimbang duka. Aku lebih suka tunjukkan pada mereka senyum bahagia bukan airmata bertanda duka atau nestapa. Aku tau kepada siapa aku harus berbagi cerita.
Tapi kali ini kamu beruntung. Aku ingin kamu bisa menjaga sebuah rahasia. Akan ku beri tahu sepenggal episode hidupku yang takkan pernah kulupa, yang selama ini kupendam sendiri saja.
Tapi sebelumnya tolong buka hati buka mata. Aku bukan sedang ingin berbagi lara. Aku ingin kamu bisa menangkap pesan yang kan ku bawa.
Kisah ini terjadi 7 tahun yang lalu, saat aku masih duduk di bangku SMA. Kisah ini tentang sesuatu yang amat berharga. Bukan rupiah bukan juga perhiasan mewah. Tapi ini tentang Ia yang kupanggil AYAH.
Pada saat SMA, ada satu masa dimana aku sering sekali tidak masuk sekolah. Atau datang telat tapi pulang selalu paling cepat. Sikapku banyak berubah. Tentu meninggalkan tanda tanya besar bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga guru-guru di sekolah.
Ayah, sosok yang selama ini selalu terlihat gagah. Kali ini harus terbaring lemah di atas kasur Rumah Sakit, menghadapi penyakit berat yang sedang Allah uji ia dengannya.
Ya, Ayah adalah alasan kenapa belakangan ini aku sering tidak masuk sekolah atau tiba-tiba pulang sekolah sebelum waktunya. Karena saat kondisi Ayah seperti itu, beliau hanya ingin ditemani olehku dan enggan jauh-jauh dariku.
Aku yang mengurus semua urusan ayah. Baik itu urusan administrasi atau operasional. Bolak balik mengambil darah di PMI, keluar masuk dari apotek satu ke apotek yang lainnya, keliling kota hanya untuk mencari obat khusus Ayah dan segudang urusan lainnya. Bahkan tak jarang aku berangkat sekolah langsung dari Rumah sakit. Saat itu aku tak mengenal waktu. Mau aku terbakar panas terik matahari atau ditusuk-tusuk dinginnya malam. Semua aku lakukan sebagai wujud baktiku dan karena Ayah adalah cinta pertamaku.
Kemana saudara-saudaraku yang lainnya? Masing-masing sudah bagi tugas. Dan soal kecekatan akulah yang paling bisa diandalkan.
Walaupun semangatku selalu membara tapi tubuhku tak bisa berdusta. Tubuhku lelah. Pernah aku diusir petugas kebersihan karena lelah tertidur di emperan Rumah Sakit. Tak jarang juga aku tertidur di ruang tunggu Rumah Sakit. Misalnya saat mengantri untuk mengambil hasil Lab darah, atau ketika menemani Ayah diterapi dengan butiran-butiran itu. Sakit katanya. Butiran-butiran yang menjadi sahabat Ayah belakangan ini. “Tak begitu baik memang, tapi tak juga bisa ditinggalkan.” Begitu cakap sang dokter soal terapi itu.
Dari sekian banyak civitas di sekolah, yang kuberi tahu soal ini hanyalah Abah. Abah adalah guru ngajiku sejak aku masih sekolah dasar sampai sekarang. Bukan sekedar guru, tapi Abah sudah seperti orang tuaku. Dan kebetulan waktu masa-masa ini, Abah adalah wali kelasku di sekolah. Karena memang profesi asli Abah adalah guru di SMA aku ini.
“Tapi Abah jangan beri tahu siapa-siapa yaa.” Pesanku untuk Abah.
Bagaimana dengan yang lain? Aku lebih senang menjawab mereka dengan senyuman. Kamu ingin menyebutku munafik? Well.. at least people don’t have to be worry about problems I have behind.
Tertutupnya aku dari teman-teman soal hal ini, menimbulkan spekulasi beragam dari mereka. Mereka bilang aku berubah. Mereka mulai membicarakanku di belakang, mencapku sebagai anak yang pemalas dan tukang bolos. Tapi aku diam saja, tahan untuk tidak menjawabnya.
Guru BK pun memanggilku ke ruangannya. Dan saat dia mulai bertanya, jawabku singkat saja, “Kenapa bapak tidak bertanya pada wali kelas saya? Maaf saya tidak bisa cerita pak.”
Sungguh aku tau itu bukan jawaban yang baik. Tapi maafkan aku. Aku memang benar-benar tidak bisa cerita. Tidak. Karena yang aku butuhkan adalah ketenangan bukan belas kasihan. Ketika sedikit saja aku bercerita, kuyakin mereka akan makin banyak bertanya. Mulai menatapku dengan mata penuh belasungkawa. Aku tidak suka itu.
Aku bisa pulang dari sekolah sebelum waktunya karena aku bekerja sama dengan Wakasek Kesiswaan. Mau tidak mau Ku beri tahu ia perihal Ayah yang sedang sakit. Kutunjukkan padanya surat panggilan dokter dari rumah sakit. Dan beliau lah yang selalu membukakan gerbang sekolah untukku. Satpam pun sampai dibuat bingung olehku. Pikirnya kenapa aku bisa mudah sekali pulang sekolah sebelum waktunya. Tapi untungnya dia tak banyak tanya.
Pernah suatu hari saat aku di sekolah, aku ditelfon karena Ayah dalam keadaan genting. Cepat-cepat aku merapihkan buku, menuruni satupersatu anak tangga dan berlari berusaha meninggalkan sekolah dengan menggendong tas ransel yang penuh, sambil tangan kananku menahan kerudung yang terbang-terbangan karena cepatnya aku berlari, sementara tangan kiriku sesekali membenarkan posisi kacamata yang hampir terjatuh. Tapi sial, semua gerbang benar-benar dikunci dan tak kutemukan Wakasek di ruangannya.
“Abah, Ayah kritis. Riri mau ke Rumah Sakit tapi gerbang dikunci semua. Wakasek nggak ada”. Dengan nada panik aku menghubungi Abah.
“Ke samping TU ya, buka pager nya itu. Keluar lewat masjid nanti sama Abah. Abah juga mau sholat dhuha di Masjid.” Abah memberiku solusi.
Akhirnya aku berhasil keluar lewat masjid dibantu Abah. Tapi setelah berhasil keluar, ada masalah kedua. Bagaimana aku akan pergi ke Rumah Sakit? Motorku tak mungkin bisa keluar lewat masjid juga. Akhirnya Abah yang super baik itu mencarikan untukku motor yang bisa dipinjam. Ah, betapa besarnya hutang budiku pada Abah.
Seiring berjalannya waktu, Faisal teman dekatku di Paskibra menaruh curiga. Ia mendesakku untuk bercerita apa adanya. Akhirnya mau tak mau aku mulai mengatakan kepada Faisal yang sebenarnya. Dan ketika aku selesai bercerita, dia kaget sekaget-kagetnya. Dia tak menyangka. Dia juga kecewa kenapa aku tidak memberitahunya sejak lama. Sejak itu dia selalu bersedia membantuku. Setiap ada kabar genting tentang Ayah, Faisal selalu bersedia mengantarku. Selalu dengan kecepatan penuh Faisal mengantarkanku ke Rumah sakit.
Selain mereka bertiga dan keluarga, tak ada lagi yang mengetahui perihal sakitnya ayah.
Sampai tiba waktunya dimana sekolah akan mengadakan rihlah. Aku dilema, antara ikut atau tidak ya. Sebenarnya ibu sudah melarangku untuk ikut, tapi celakanya hari itu aku lebih menuruti egoku.
“Tapi bu, aku kan pengen juga jalan-jalan bareng temen-temen.” Sambil memajukan bibir aku memasang muka memelas.
“Yasudah, tapi kalau ada apa-apa ibu nggak mau ngasih tau loh ya.” Jawab ibu pasrah dengan nada sedikit mengancam.
Awalnya perjalanan rihlah terasa menyenangkan. Tapi entah kenapa sepanjang perjalanan selalu terbayang di benakku sosok Ayah yang sedang terbaring lemah.
Selama perjalanan, aku tak berhenti panjatkan doa untuk ayah. Setidaknya walaupun ragaku jauh dari ayah tapi doaku bisa dekat.
“Ya Allah, kalau memang ayah akan sehat dan sembuh, maka sembuhkanlah segera ya Allah. Tapi jika Engkau ingin sembuhkan ayah dalam dekapanmu, maka kami sekeluarga ikhlas. Karena kami tidak tega melihat ayah sakit terus….” Ucapku lirih meminta pada Allah.
Entah saat doa keberapa dan entah bisikan dari mana, aku tiba-tiba merasa kalau ayah sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi aku berusaha tetap tenang, menganggap perasaan itu tidak benar adanya.
Sampai akhirnya, saat bis sedang di jalan tol hendak melanjutkan perjalanan ke tujuan rihlah selanjutnya, tiba-tiba telfonku berdering. Mbak menelfon ku. Dan di ujung telfon tak terdengar apa-apa kecuali suara Mbak menangis. Tanpa basa basi aku langsung tahu kalau Ayah memang benar sudah tiada. Duniaku berhenti sementara. Rasa sedih itu merambat masuk ke setiap urat nadiku untuk kemudian menjebol tanggul air mataku. Tak kuasa aku mencegahnya.
Aku berusaha menghubungi Abah. Tapi Abah tak menjawab. Sampai akhirnya bis berhenti. Awalnya aku tidak tahu kenapa dan untuk keperluan apa bis ini berhenti.
Aku berdiri menghampiri guru-guru pembimbing, hendak pamit pulang karena Ayah meninggal. Tapi ternyata mereka sudah tahu kabarnya, karena ada salah satu keluargaku yang sudah menghubungi pihak sekolah. Beberapa guru dan teman ikut menangis saat itu juga. Mereka kaget sekaligus tidak percaya. Dan akhirnya mereka sadar telah menemukan jawaban dari prasangka buruk mereka kepadaku selama ini.
“Kamu kok nggak cerita sama ibu sih nak? Ibu juga kok ya gak kepikiran tanya ke kamu beberapa hari ini.” Sambil menyeka air matanya Bu Mala menghampiriku. Bu Mala memang salah satu guru yang paling dekat denganku.
Tapi aku tidak berniat menjawab pertanyaannya pada saat itu. Karena yang kuinginkan hanyalah bisa pulang ke rumah secepatnya.
Bergegas aku mengambil tas bawaanku. “Kalian tolong maafkan ya kalau aku atau ayahku banyak salah.” Sambil terisak aku berjalan turun dari bis, meninggalkan rombongan.
Ditemani tiga orang guru, aku memberhentikan taksi di ujung jalan. Dan dalam hitungan detik, supir taksi yang mengikuti permintaanku sudah menginjak pedal gasnya dalam-dalam.
Saat itu rumahku dipenuhi isak tangis seluruh keluarga.
“Depan keluarga aku harus berusaha sebisa mungkin untuk terlihat baik-baik saja.” Batinku berbicara.
Saat aku sampai di rumah, semuanya lega. Karena sejak tadi aku lah yang di tunggu-tunggu supaya mereka bisa memulai prosesi pengurusan jenazah Ayah.
Setelah semua prosesi selesai, jenazah Ayah siap ditandu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Masih tergambar jelas dalam memoriku bagaimana tubuh Ayah saat itu yang hanya terbujur kaku. Dan itu adalah kali terakhir aku melihat wujud Cinta Pertamaku di dunia untuk selamanya. Ribuan kata mendadak bisu saat diminta untuk menceritakan bagaimana perasaanku saat itu.
Seharusnya hari itu panas, tapi tiba-tiba awan menjadi mendung. Mungkin langit pun ikut berkabung atas apa yang sedang keluargaku alami. Ayah diantarkan ke liang lahadnya dengan deraian airmata.
Prosesi pemakaman selesai, Ayah sudah beristirahat tenang di bawah tanah. Ayah sudah tidak merasakan sakit lagi.
Semua keluarga pun sudah kembali ke rumah, meninggalkanku sendiri yang masih termenung di samping makam Ayah.
Perasaan sedih dan bersalah menyayat hatiku secara bersamaan saat itu. Kepalaku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan penuh penyesalan. “Kenapa aku yang selama ini menemani Ayah justru harus absen pada detik-detik terakhir hidupnya?” “Kenapa aku tidak bisa bimbing ayah saat sakratul maut?” “Kenapa aku terlalu egois, lebih mementingkan rihlah ketimbang menemani ayah?” “Kenapa?! Kenapa?! Padahal masih terdengar jelas di telingaku pesan ayah, “Yang sabar ya nak, tungguin ayah disini.”
Aku tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan air mata pun sudah tak mampu mengekspresikan perasakanku saat itu. Aku memendam rasa sakit itu dalam dada. Sakit sekali rasanya. Saaakiiiiit sekali. Ingin sekali aku berteriak sekencang-kecang nya. Tapi setelah kupikir lagi, buat apa?
Tak berselang lama gerimis pun datang. Semakin deras gerimis itu. Air dari langit tumpah ruah seirama dengan air mata yang ada di ujung mataku. Akhirnya aku pamit pulang, tak bisa aku berdiam lebih lama. Dari pada aku sakit kehujanan, nanti ibu akan lebih kerepotan lagi.
Sesampainya aku di rumah, aku berusaha untuk kembali terlihat tegar. Semua masih tenggelam dalam tangisan, terlebih adik dan ibuku. “Kalau aku ikut menampakkan kesedihan, siapa yang akan membesarkan hati ibu?” Fikirku dalam hati.
“Nggk sedih apa ayahmu meninggal?” Tiba-tiba seseorang bertanya padaku. Hey! Pertanyaan macam apa itu. Ingin sekali rasanya menonjok mulut orang itu. Tapi kuurungkan niat itu. Dalam hati aku berkata, “Sabar, akan banyak perubahan di keluarga dan masih banyak urusan yang harus di selesaikan.”
Keesokannya aku langsung bergrilya menyelesaikan urusan-urusan ayah. Bertanya pada seluruh kerabat dan rekan kerja Ayah, apa Ayah punya hutang yang belum di bayar atau janji yang belum terselesaikan. Sekaligus meminta maaf atas kesalahan-kesalahan Ayah selama beliau hidup. Yang sedikit rumit adalah saat mengurus catatan sipil, balik nama hak milik, surat ahli waris dan berbagai macam surat lainnya dari kantor ayah.
Karena ibu sedang dalam masa iddah, maka semua itu aku urus sendiri. Sampai akhirnya aku jatuh sakit dan harus di opname di rumah sakit.
Sejak saat itu mengunjungi makam adalah kegiatan favoritku. setiap kamis, jumat dan sabtu selalu kusempatkan waktu untuk datang ke makam. Tidak banyak yang kulakukan. Hanya sekedar membersihkan rumput di sekitar makam ayah atau menikmati keheningan dan sejuknya suasana pemakaman.
Tahun demi tahun pun berlalu. Kupikir sudah saatnya untuk berbagi kisah lamaku. Dan apa kau tahu? Saat menulis cerita ini aku menangis tersedu-sedu. Tak kuasa aku menahan haru karena berhasil melewati masa-masa itu.
Sekarang tugasku tinggal mendoakan Ayah supaya mendapatkan tempat terbaik di sisiNya. Juga berusaha merealisasikan pesan ayah yang beliau sampaikan dua hari sebelum hari kepergiannya, “Riri, besok kamu harus bisa jadi guru yang baik ya. Kejar cita-citamu. Kamu harus bisa bermanfaat untuk orang banyak.”

Ditulis berdasarkan kisah nyata seorang sahabat.
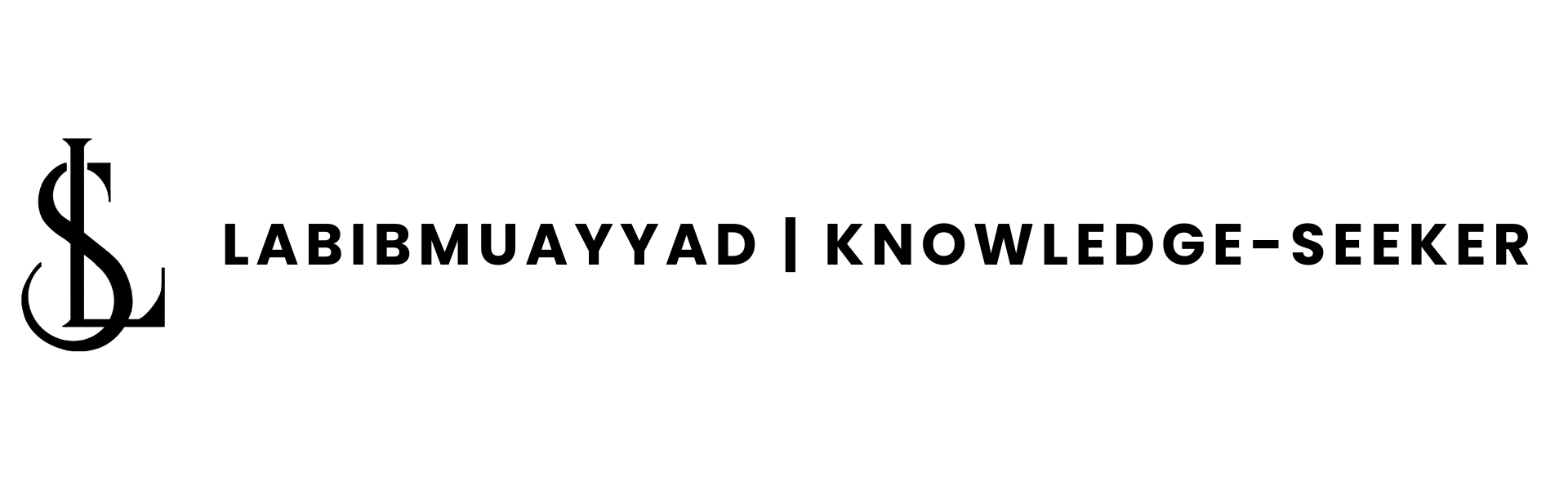
Entah ini ceritanya yang bagus, atau memang Labib pintar mengetiknya. Barakallahu fik bro , lanjutkan karya-karya nya
Terimakasih Mbak
Samasama
A.
Dan apa kau tahu? Saat menulis cerita ini aku menangis tersedu-sedu. Tak kuasa aku menahan haru karena berhasil melewati masa-masa itu..
B.
“ditulis berdasarkan kisah nyata seorang teman..”
A B: kontradiksi?
______\\|//_______
premis:
A: ‘pencerita’ yang baik
B: ‘pendengar’ yang baik
kesimpulan:
kamu anak yang baik 😚
MasyaAllah, mantap bib.
Faedah ada.
Sastra ada.
Panutanku emang.
Semangattt bib…
[…] Jika belum baca cerita sebelumnya, maka bisa dibaca di https://labibmuayyad.wordpress.com/2019/05/18/untuknya/ […]